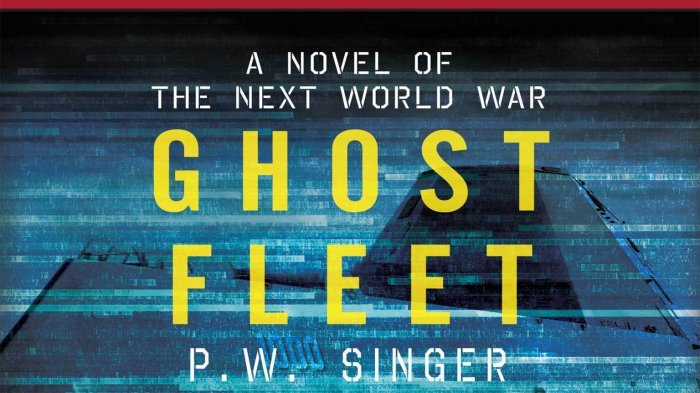Dalam sebuah ceramah yang mungkin dianggap sebagai pidato politik, menyusul makin hebohnya wacana seputar pemilu nasional 2019, Prabowo Subianto, kandidat pelawan presiden petahana sekaligus pesaing beratnya dalam pemilu 2014, menyinggung sebuah ramalan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030.
Sebagaimana biasa, pihak oponen segera mencari[-cari] celah kelemahan pidato mantan menantu Presiden Suharto itu, khususnya di kalangan mereka yang memendam sentimen negatif tinggi terhadap Orde Baru dan TNI. Maka, sebagaimana telah sama kita ketahui melalui medsos dan media lainnya, rupanya refleksi Prabowo tentang masa depan Indonesia yang dianggap mengandung nada pesimis itu merujuk kepada sebuah novel karangan P.W. Singer dan August Cole, Ghost Fleet, terbitan Houghton Miffin Harcourt (Boston) tahun 2015.
Komentar-komentar para oponen Prabowo, termasuk beberapa orang yang sejauh saya ketahui sangat intelek dan mungkin sering bersentuhan dengan karya sastra dan membaca teori-teori sastra, beragam. Namun, komentar-komentar miring yang beraneka macam itu dapat diintisarikan dengan singkat: bagaimana seorang yang katanya mau mencalonkan diri menjadi presiden percaya pada sebuah cerita fiksi?
Perdebatan ini agaknya menggugah kita untuk berefleksi lebih jauh tentang kebudayaan dan pendidikan bangsa kita secara lebih dalam. Cukup jelas bahwa di ‘Zaman Now’ kini, perenungan manusia tentang hakikat kehidupan ini, termasuk dalam soal berbangsa dan bernegara, terkesan makin dangkal dan simplistis. Orang cenderung mengukur segala sesuatu dengan rasionalitas saja. Refleksi-refleksi yang merujuk teks-teks fiksional, sebagaimana dulu sering dilakukan oleh para pendiri Republik ini, baik dalam pidato-pidato maupun buku-buku yang mereka tulis, kini dianggap bodoh dan tidak masuk akal.
Prabowo dalam tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan wartawan terkait dengan pidatonya itu mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan hanya dimaksudkan sebagai peringatan agar bangsa Indonesia mawas diri, agar bangsa Indonesia waspada dan tidak lurus tabung dalam menghadapi percaturan politik dunia sekarang ini; bahwa banyak pihak dari luar yang selalu mengintai dan ingin merampok kekayaan alam Indonesia, yang tentunya menghendaki rakyat Indonesia tidak boleh makmur dan dibuat kacau terus agar tetap dapat dikuasai. “Kita bukan anti asing, kita mau bersahabat dengan asing, tapi jangan kita terlalu lugu, jangan kekayaan kita diambil tapi elitnya diam [saja]”, kata Prabowo.
Mungkin suara Prabowo menggemakan perasaan banyak anak bangsa lainnya di Republik ini, yang ingin agar nasion yang besar dan majemuk ini menata kembali kehidupan bernegara, yang akhir-akhir ini menunjukkan gejala salah urus. Jika hal ini dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin dalam dua dekade ke depan sebuah negara-bangsa yang bernama ‘Indonesia’ betul-betul akan bubar.
Namun, jauh di balik hal-hal yang bersifat politis yang diperdebatkan secara permukaan dan emosional itu, polemik mengenai pidato Prabowo itu sendiri sampai batas tertentu agaknya mencerminkan bagaimana wacana sastra dipandang oleh kalangan terpelajar kita di ‘Zaman Now’. Jangan-jangan memang sudah sangat langka, untuk tidak mengatakan tidak ada lagi, para intelektual dan poli(ti)si kita yang membaca karya-kaya sastra untuk memperluas wawasannya.
Dalam situasi yang mengarah ke ketumpulan imajinasi ini, para akademisi yang selama ini bergelut di bidang penelitian sastra – Sapardi Djoko Damono, Melani Budianta, Faruk, Dede Utomo, Diah Arimbi, Maneke Budiman, Maman S. Mahayana, Hasanuddin W.S., Sunu Wasono, Ibnu Wahyudi, untuk sekedar menyebut beberapa nama – juga tak hendak bersuara dan memberi pencerahan kepada publik. Kalangan perguruan tinggi pun diam dan tak hendak berinisiatif menjelaskan hakikat sastra dalam kehidupan manusia, termasuk dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Semua pihak jatuh ke dalam apatisme massal di tengah eforia politik ‘democrazy’ bergelimang uang haram yang kian meruyak dan makin melumpuhlayuhkan rakyat banyak.
Filusuf dan eseis Amerika Ralph Waldo Emerson mengatakan: “The world is a kingdom of illusions”. Arkian, betapa malangnya sebuah bangsa, terutama kaum intelektual dan politisinya, bila tidak memiliki refleksi dan imajinasi tentang kehidupan bangsanya: zaman lampau kini, dan masa depan. Teks sastra memainkan peran penting dalam membentuk imajinasi itu. Di negara-negara dengan tingkat literasi tinggi, dimana karya sastra menjadi ‘santapan’ sehari-hari masyarakatnya, kedewasaan berpikir bangsa itu juga menunjukkan kematangan. Orang-orang tidak mudah dihasut dan tersulut ke dalam perbalahan emosional dan remeh-temeh yang menggerus akal sehat.
Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa refleksi Prabowo Subianto tentang masa depan Indonesia yang merujuk sebuah karya fiksional adalah suatu yang langka di zaman sekarang. Kebanyakan politisi “Zaman Now” tak mengenal dunia seni pada umumnya dan sastra pada khususnya, sebagaimana tercermin dalam komentar bego pemimpin negeri ini terhadap film Dilan. Keadaannya sungguh berbeda dengan para pemimpin di zaman pergerakan yang menjadikan karya sastra sebagai bacaan sehari-hari penambah wawasan dan sebagai sumber inspirasi dalam tindak laku politik mereka.
P.W. Singer dan August Cole tentunya buka dua orang asing pertama yang membayangkan masa depan Indonesia dalam teks fiksional futuristik. Kita ingat misalnya pengarang Australia berdarah aborigin Eric Willmot dengan novelnya Below the Line (Sydney: Hutchinson Australia, 1991) yang membayangkan invasi Indonesia ke wilayah Pasifik. Bertolak belakang dengan imajinasi Singer dan Cole dalam Below the Line yang membayangkan Indonesia akan hilang dari peta negara-negara di dunia pada 2030, Willmot malah menggambarkan Indonesia begitu perkasa sehingga mengancam eksistensi Australia, negara putih di Selatan.
Meminjam kata-kata Iva Polak dalam bukunya Futuristic Worlds in Australian Aboriginal Fiction (Oxford [etc.]: Peter Lang, 2017), karya Willmot dan sejumlah pengarang Australia lainnya yang berdarah Aborigin mencerminkan “the authors’ cultural memory and experience of having survived the ‘end of world’ brought about by colonisation.” Namun, sebagaimana diasumsikan dalam teori resepsi sastra, cultural memory yang diekspresikan oleh seorang pengarang dalam karyanya akan memenuhi horizon harapan (horizon ofexpectation) para pembaca sembari tetap memberikan kemungkinan sebaliknya kepada pembaca yang lain. Pada momen inilah karya sastra akan selalu mengalami interpretasi dan pada saat yang sama sang pengarang sebenarnya ‘sudah mati’ dan tak mampu mengendalikan makna karya yang ditulisnya. Dalam konteks ini, menyudutkan Prabowo dengan meminta keterangan Singer dan Cole atas makna Ghost Fleet yang sesungguhnya hanyalah sebuah ketololan belaka.
Lebih jauh lagi, kita tentu dapat memberi interpretasi yang bukan manasuka (arbitrer) terhadap dua karya orang asing yang menggambarkan Indonesia secara kontradiktif tersebut berdasarkan teori sosiologi dan psikologi sastra.
Pengarang berdarah aborigin Eric Willmot membayangkan kebangkitan kaum pribumi (natives) di kawasan Asia-Pasifik tempat nenek moyangnya menjadi minoritas yang ditindas oleh para pendatang dari Eropa di tanah ‘Terra Incognita’. Suara dalam Below the Line sampai batas tertentu mengandung nada antipoda terhadap wacana mainstream dalam kesusastraan Australia yang cenderung menganjungkan wacana (yang memihak) kaum putih. Ini dapat dianalogikan dengan dikotomi Balai Poestaka di satu pihak dan percetakan-percetakan pribumi yang memproduksi roman-roman Medan di pihak lain di zaman di Hindia Belanda pada Zaman Kolonial.
Imajinasi Singer dan Cole dalam Ghost Fleet sampai batas tertentu merepresentasikan superioritas sekaligus phobia Amerika terhadap kekuatan asing yang menjadi competitor utamanya di bidang politik dan ekonomi, khsusnya Cina. Walau dibungkus dengan kalimat “The following was inspired by real-world trends and technologies. But, ultimately, it is a work of fiction, not prediction” (kursif dari Suryadi) – sebuah catatan marginalia yang formulaik dan selalu muncul dalam teks-teks novel/roman dalam nada yang berbeda dari zaman ke zaman (bandingkan misalnya dengan: “Novel ini adalah cerita fiksi belaka, jika ada nama dan tempat serta kejadian yang sama atau mirip terulas dalam novel ini, itu hanyalah kebetulanbelaka” atau yang berasal dari periode yang lebih awal yang justru bernada sebaliknya, mendekatkan fiksi dengan kenyataaan: “Soeatoe tjerita jang telah kedjadian di Djawa Koelon” (dikutip dari judul roman Cina Peranakan Annemer Tan Ong Koan atawa Binasa di Tangan Laen Bangsa karya Liem Khoen Giok, Batavia: Tan Thian Soe, 1919) – kita dapat memberi interpretasi bahwa itu adalah semacam ‘tipuan’ (trick) untuk mengacaukan horizon harapan pembaca sekaligus helah pengarang untuk ‘menyembunyikan’ fakta dalam teks fiksi supaya semuanya dianggap fantasi. Dengan kata lain, marginalia yang formulaik seperti itu berfungsi menjaga tegangan (sekaligus juga menjaga rahasia) antara yang nyata dan yang khayali dalam teks-teks fiksional. Hakikat formula tersebut adalah sebuah cara untuk mengelabui pembaca dari kenyataan yang sebenarnya.
Baik Ghost Fleet maupun Below the Linemengandung pesan-pesan literer yang tak vacuum dari realitas. Sememangnyalah karya sastra bukan jatuh begitu saja dari langit. Sebuah teks literer selalu memiliki landasan faktual dalam dunia nyata. Dengan pendekatan semiotika, akan banyak hal yang dapat diungkapkan dalam kedua karya tersebut.
Bagi para politisi Indonesia di ‘Zaman Now’, membaca perspektif dan imajinasi bangsa asing tentang negeri ini mestinya adalah suatu keniscayaan, baik melalui buku-buku ilmiah maupun karya sastra, sebagaimana dulu dipraktekkan oleh para founding fathers negara ini. Jika terus hanya bersiarak dalam perang pernyataan di twitter yang makin tidak berkeruncingan, sogok-menyogok memakai uang hasil korupsi di bilik-bilik hotel mewah yang kian masif, toleransi beragama yang makin menipis, bully-mem-bully yang makin tak mengindahkan moral dan adat sopan santun di laman-laman facebook dan di ruang-ruang publik, yang semuanya makin mengauskan akal sehat, bukan tidak mungkin Indonesia akan tinggal cangkangnya saja di tahun 2030 (atau 2037?), sebagaimana nasib Uni Soviet yang lenyap hanya 7 tahun lebih lama dari ramalan Andrei Amalrik dalam bukunya Will the Soviet Union Survive untuil 1984?(New York [etc.]: Harper & Row, 1970).
Membuat analogi dari sebuah ungkapan bijak dalam ajaran Islam, abadinya Indonesia sampai akhir zaman adalah karena karunia Tuhan. Sebaliknya, bila negara ini hancur dan lenyap pada suatu saat nanti, itu jelas karena kesalahan anak bangsanya sendiri.[ ]
Matthias de Vrieshof, Maret 2018.
Dr. Suryadi | LIAS – SAS Indonesië, Universiteit Leiden, Belanda. Esai ini diterbitkan di harian Haluan, Selasa 27 Maret 2018 (Kabarlain)